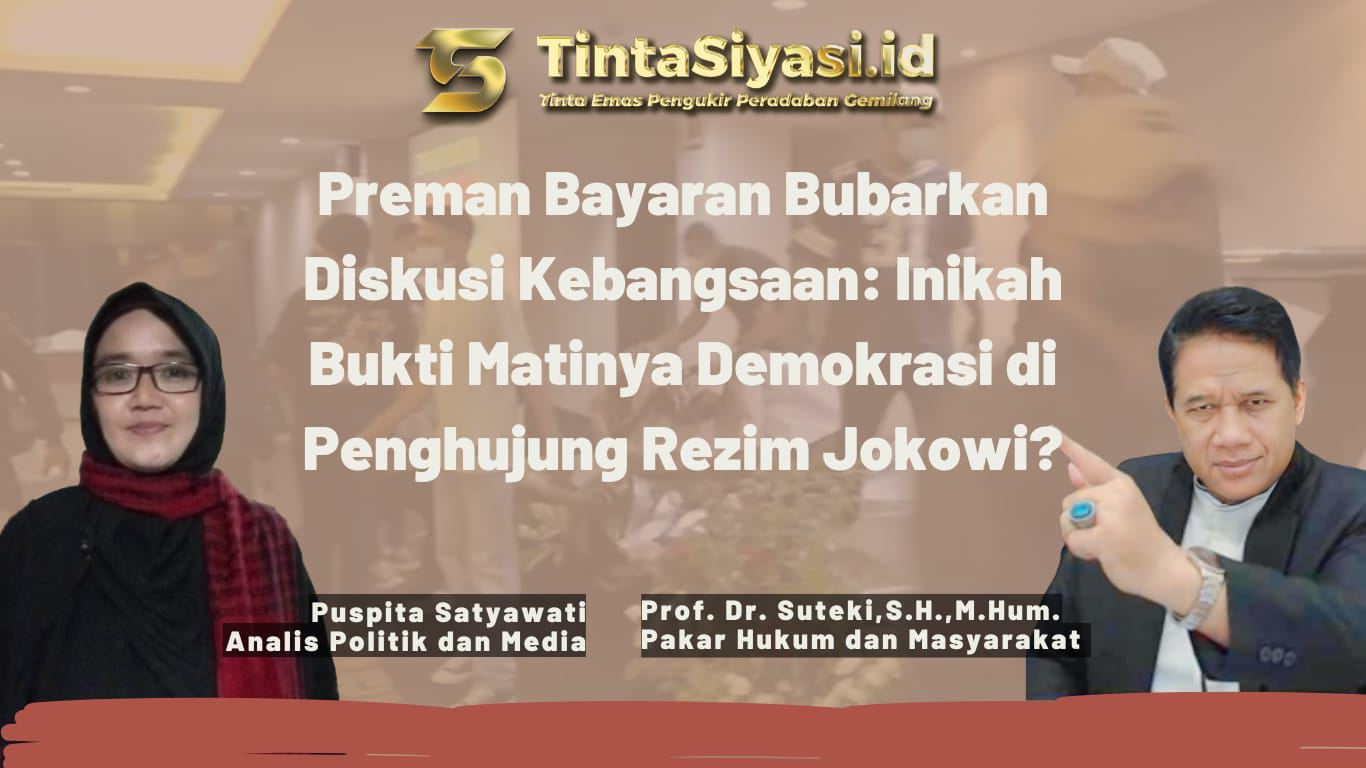TintaSiyasi.id -- Sungguh bar-bar ala preman bayaran! Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024), terpaksa dibubarkan setelah sekelompok orang tak dikenal menyerang acara tersebut. Aksi pembubaran paksa itu berlangsung anarkis. Para pelaku merusak panggung, merobek backdrop, mematahkan tiang mikrofon, dan mengancam peserta yang baru hadir di lokasi.
Acara yang sedianya dirancang sebagai forum dialog antara diaspora Indonesia di luar negeri dengan sejumlah tokoh dan aktivis membahas isu-isu kebangsaan ini menghadirkan narasumber seperti Din Syamsuddin, Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadhilah, dan Sunarko, serta Ketua dan Sekjen Forum Tanah Air, Tata Kesantra dan Ida N. Kusdianti. Anehnya, meski aparat kepolisian berada di lokasi, massa perusuh terlihat leluasa beraksi tanpa upaya pembubaran yang tegas dari pihak berwenang.
Din Syamsuddin menyebut peristiwa brutal tersebut merupakan refleksi dari kejahatan demokrasi yang dilakukan rezim penguasa terakhir ini (rmol.id, 28/9/2024). Bila benar dugaan beberapa pihak, ada 'oknum' penguasa bermain di balik aksi premanisme tersebut, itu berarti penguasa kian otoriter dan menindas oposisi. Maka dalam kondisi ini, sejatinya demokrasi tengah mati. Inilah paradoks demokrasi. Ia berpotensi 'dibunuh' oleh pemimpin yang dilahirkan oleh sistem demokrasi itu sendiri.
Pembubaran Paksa terhadap Diskusi Kebangsaan: Kekuasaan Otoriter, Tanda Demokrasi Mati
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengatakan, tindakan premanisme yang membubarkan diskusi kebangsaan harus diproses secara hukum. Tanpa menunggu laporan masyarakat atau penyelenggara karena di lokasi kejadian ada aparat kepolisian. Menurutnya, kalau tidak diproses hukum maka publik bisa beranggapan polisi membiarkan tindakan pidana tersebut. Ini akan berujung penilaian buruk pada institusi Polri serta menjadi preseden penggunaan kekerasan yang merusak tatanan Indonesia sebagai negara hukum (tempo.co, 28/9/2024).
Dugaan beberapa pihak adanya keterlibatan oknum penguasa di balik aksi preman bayaran tersebut, mengingatkan kami tentang sebuah buku berjudul How Democracies Die karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, dua orang ilmuwan politik dari Harvard University.
Di bagian pendahuluan, keduanya memaparkan bagaimana demokrasi bisa mati. "But there is another way to break a democracy". Siapa pembunuh demokrasi itu? Pembunuhnya bukan para jenderal tiran, diktator, tetapi penguasa yang terpilih dalam sistem demokrasi itu sendiri. It is less dramatic but equally destructive (p. 3).
Ziblatt dan Levitsky membeberkan banyak contoh; dari Chávez di Venezuela, pemimpin terpilih di Georgia, Hungaria, Nicaragua, Peru, Filipina, Polandia, Russia, Sri Lanka, Turki, Ukraina, dan tentu saja AS sendiri. Semua pemimpin tadi membunuh demokrasi secara perlahan.
Ternyata demokrasi juga mengalami senjakala mendekati lonceng kematiannya. Apakah mungkin penguasa Indonesia yang mengaku sebagai penguasa demokratis berdasar Pancasila saat ini termasuk yang sedang membunuh sistem yang dipilih dan diciptakannnya sendiri?
Steven dan Daniel mengatakan tidak semua pemimpin terpilih tadi memiliki track record represif dan otoriter. Memang ada yang sejak awal tampak otoriter seperti Hitler dan Chávez. Tapi banyak juga yang awalnya berwajah polos dan lugu, pelan tapi pasti lalu menjadi otoriter setelah memimpin demi mempertahankan kekuasaannya.
Keduanya lalu memberikan indikator sistem kepemimpinan itu otoriter atau demokratis. Ada empat indikator otoritarianisme yang disebut "Four Key Indicators of Authoritarian Behavior". Untuk mengetes indikator otoritarianisme itu digunakan "litmus test" (p. 23-24). Keempat indikator itu adalah:
Pertama, reject of (or weak commitment to) democratic rule of the game (Penolakan (atau lemah komitmen) terhadap sendi-sendi demokrasi).
Parameternya:
(1) Apakah mereka suka mengubah-ubah UU?
(2) Apakah mereka melarang organisasi tertentu?
(3) Apakah mereka membatasi hak-hak politik warga negara?
Peristiwa perubahan UU KPK, UU Minerba, 79 UU dalam UU Omnibus Law yang disebut UU Kejar Tayang dan legitimasinya rendah lantaran ditolak oleh "buanyak pihak" mungkin parameter pertama terpenuhi. Parameter kedua tampaknya juga terpenuhi dengan kejadian pencabutan badan hukum dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017 dan para aktivisnya "dipersekusi".
Pun penangkapan 8 aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diduga terkait demonstrasi tolak UU Omnibus Law CLBK (Cipta Lapangan Bisnis dan Kerja) yang berakhir rusuh. Diduga terjadi pembatasan hak dasar politik untuk berkumpul dan menyatakan pendapat yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi itu sendiri.
Kedua, denial of the legitimacy of political opponent (penolakan terhadap legitimasi oposisi).
Parameternya antara lain: apakah menyematkan lawan politik mereka dengan sebutan-sebutan subversif, mengancam asas dan ideologi negara? Apakah mereka mengkriminalisasi lawan-lawan politik mereka dengan berbagai tuduhan yang mengada-ada?
Kita ingat, banyak orang kritis di negeri ini yang dituduh terpapar radikalisme, terpapar ideologi "khilafahisme", makar, anti Pancasila dan anti NKRI, serta para ustaz dan ulama yang "dikriminalisasi". Kini aksi premanisme membubarkan diskusi kebangsaan terkesan membuktikan adanya ancaman terhadap kekuasaan yang tengah berlangsung.
Ketiga, toleration or encouragement of violence (toleransi, membiarkan atau mendorong adanya aksi kekerasan).
Parameternya antara lain: apakah mereka memiliki hubungan dengan semacam organisasi paramiliter yang cenderung menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri? Selama ini ada ormas kepemudaan berseragam "militer" yang acapkali "mempersekusi", membubarkan pengajian, serta bertindak seolah mendudukkan diri sebagai polisi, jaksa dan hakim sekaligus. Apa yang terjadi di Pasuruan dan Surabaya beberapa waktu lalu menjadi indikator dugaan hubungan antara paramiliter dengan kekuasaan.
Tugas menahan, menghentikan kegiatan warga itu adalah tugas aparat penegak hukum, bukan tugas ormas apalagi preman bayaran. Namun kita saksikan penguasa terkesan hanya diam dan seolah menyetujui semuanya. Inikah bukti parameter indikator ketiga terpenuhi?
Keempat, readiness to curtail civil liberties of opponent, including media (kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil).
Parameter di antaranya:
(1) Apakah mereka mendukung (atau membuat) UU yang membatasi kebebasan sipil, terutama hak-hak politik dan menyampaikan pendapat?
(2) Apakah mereka melarang tema-tema tertentu?
Diterbitkannya UU Ormas, RUU HIP, serta berbagai kebijakan penguasa yang melarang pembahasan tema tertentu misalnya tentang khilafah karena dianggap mengancam Pancasila dan NKRI, sementara khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam tentang Fikih Siyasah yang boleh dipelajari dan didakwahkan sebagaimana shalat, zakat, haji, dan lain-lain menjadi bukti parameter indikator keempat ini.
Ancaman psikologis terhadap para aktivis pendakwah, ustaz dan lain-lain dengan narasi terpapar radikalisme cukup menghambat hak politik untuk menyampaikan pendapat. Pun penahanan aktivis KAMI pada Oktober 2020 dan aksi preman membubarkan diskusi kebangsaan (28/9/2024) juga sebagai indikasi pembatasan bahkan ancaman terhadap hak menyatakan pendapat dan berkumpul. Tidakkah ini juga menunjukkan terpenuhinya parameter otoritarianisme indikator keempat ini?
Keempat indikator itu mungkin terpenuhi semua atau sebagian terpenuhi, maka dapat disebut bahwa suatu negara demokrasi telah mengarah kepada lonceng kematiannya. Jadi, jika jawaban dari semua pertanyaan yang menjadi parameter setiap indikator di atas adalah ya, maka patut diduga bahwa rezim saat ini termasuk otoriter dan represif.
Dampak Matinya Demokrasi terhadap Kelangsungan Hidup Penyelenggaraan Negara di Indonesia
Aksi preman bayaran yang membubarkan diskusi kebangsaan dinilai sebagai upaya pemberangusan kebebasan berpendapat. Padahal di era pemerintahan siapa pun dan kapan pun, kritik publik tak bisa dihindari. Dalam mengelola urusan rakyat, kebijakan penguasa berpotensi tak memuaskan semua pihak. Pun sebagai manusia, kepemimpinannya pasti diliputi kekurangan. Di sinilah kritik hadir sebagai katarsis kekuasaan.
Terkait cara merespons kritik yang ditujukan padanya, rezim hari ini sering mendapat sorotan publik. Banyak pihak membandingkan sikap rezim saat ini dengan sebelumnya yang bermuara pada kesimpulan ‘emoh’ dikritik dan lebih emosional. Meski acapkali menunjukkan pesan positif untuk bersedia dikritik, namun di sisi lain menghantam oposisi yang lantang mengkritik kekuasaan.
Bila demokrasi mati akibat ulah penguasa itu sendiri yang otoriter, maka dampak yang terjadi terhadap kelangsungan hidup penyelenggaraan negara di Indonesia adalah;
Pertama, penyelenggaraan negara lebih berporos pada kehendak segelintir manusia. Selama ini sudah bukan rahasia lagi bila pengelolaan negara dikuasai oleh kaum Peng-Peng (penguasa-pengusaha). Politik dijalankan bukan demi kemaslahatan rakyat tapi untuk kepentingan oligarki.
Kedua, trust rakyat pada penguasa kian turun. Bagaimana mungkin rakyat memberikan kepercayaan pada pemimpin yang tidak menjadikan rakyat sebagai poros perhatian atas tugas-tugas mengelola negara?
Ketiga, Pembangkangan sipil bisa melanda. Pembangkangan sipil adalah penolakan untuk mematuhi hukum tertentu, tuntutan, dan perintah dari suatu pemerintah atau kekuatan kekuasaan. Pembangkangan sipil merupakan salah satu yang dilakukan rakyat untuk memberontak terhadap apa yang mereka anggap sebagai hukum yang tidak adil.
Keempat, polarisasi sedemikan parah di tengah masyarakat. Masyarakat terbagi antara yang pro dan kontra terhadap rezim. Dan kemungkinan terburuknya bisa terjadi perang sipil.
Kelima, memicu people power yang bertujuan menggulingkan kekuasaan otoriter. Bila ini terjadi, kondisi chaos pun akan tak terhindarkan.
Demikianlah dampak yang mungkin terjadi terhadap penyelenggaraan negara bila demokrasi mati. Bila demokrasi telah mati, mestinya bangsa ini rela meninggalkan sistem politik yang keberadaannya telah cacat sejak lahir ini dan beralih pada sistem politik yang benar dan sesuai fitrah manusia. Yaitu sistem Islam yang menerapkan hukum Allah SWT, dzat yang paling memahami manusia dan paling mengerti solusi terbaik bagi masalah apa pun yang menimpa makhluk-Nya.
Strategi Pengelolaan Kritik dalam Komunikasi Politik yang Menjamin Kebebasan Rakyat Menyatakan Pendapat
Jika demokrasi dengan wajah aslinya yaitu tirani minoritas atas mayoritas telah melahirkan penguasa anti kritik, maka Islam melalui penerapan sistem pemerintahan khilafah justru membuka ruang kritik bagi masyarakat. Bahkan dalam Islam, kritik termasuk ajaran Islam yaitu amar makruf nahi mungkar, sebagaimana firman Allah Swt, “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran: 110)
Rasulullah Saw menyatakan dengan spesifik kewajiban serta keutamaan melakukan muhasabah (koreksi) kepada penguasa. Al-Thariq menuturkan sebuah riwayat, “Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw seraya bertanya, ‘Jihad apa yang paling utama?’ Rasulullah Saw menjawab, ‘Kalimat hak (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang zalim.'” (HR. Imam Ahmad)
Muhasabah atau kritik terhadap penguasa merupakan bagian dari syariat Islam yang agung. Dengan muhasabah, tegaknya Islam dalam negara akan terjaga dan membawa keberkahan. Seorang pemimpin yang beragama Islam harusnya tak perlu alergi kritik. Terlebih jika sampai membungkam lawan politik dengan kebijakan represif. Kritik bukanlah ancaman. Bahkan dibutuhkan sebagai standar optimalisasi kinerja pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan dunia-akhirat.
Kritik umat terhadap penguasa adalah sunah Rasul dan tabiat dalam Islam. Kritik menjadi saluran komunikasi publik sekaligus bentuk cinta rakyat terhadap pemimpin agar tak tergelincir pada keharaman yang dimurkai Allah SWT. Secara umum, Islam mengatur etika dalam menyampaikan kritikan, di antaranya;
Pertama, menasihati dan mengkritik kebijakan penguasa dalam kerangka menjalankan kewajiban. Pun sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT dan kemaslahatan umat. Bukan demi kepentingan pribadi/kelompok. Kita tidak boleh melancarkan kritik dengan tujuan menonjolkan diri, termotivasi oleh hasad (kedengkian) atau berbagai tendensi tertentu, namun semata-mata untuk memperoleh ridha Allah ta’ala.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam al-Fatawa mengatakan, “Wajib bagi setiap orang yang memerintahkan kebaikan dan mengingkari kemungkaran berlaku ikhlas dalam tindakannya dan menyadari bahwa tindakannya tersebut adalah ketaatan kepada Allah. Dia berniat untuk memperbaiki kondisi orang lain dan menegakkan hujah atasnya. Bukan untuk mencari kedudukan bagi diri dan kelompok, tidak pula untuk melecehkan orang lain."
Kedua, mengkritik harus disertai ilmu. Artinya, kritikan benar-benar didasari dengan ilmu di bidangnya. Kita tidak boleh mengritik tanpa ilmu dan basirah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam al-Fatawa mengatakan, “Hendaknya setiap orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar adalah seorang yang alim terhadap apa yang dia perintahkan dan dia larang.”
Hal ini akan menghindarkan seorang Muslim bersikap ‘asal njeplak’, jauh dari perilaku mencela dan menghujat. Ia mengkritik berdasarkan ilmu, baik berlandaskan dalil agama maupun data secara fakta dan keilmuan yang menunjang.
Ketiga, tidak diperbolehkan mengkritik penguasa dengan menghina pribadi penguasa itu, sebab semua yang terkait fisik adalah ciptaan Allah SWT yang tidak boleh dihina. Misalnya, fisiknya hitam, putih, kurus, gemuk, keriting, dan sebagainya. Ranah yang dikritik adalah kebijakan/aturan yang dibuat penguasa saat melanggar hukum Allah SWT dan atau tidak memenuhi hak umat yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya.
Keempat, menyampaikan dengan bahasa ahsan sesuai adab Islam. Kritik adalah bagian amar makruf nahi mungkar atau dakwah. Dalam aktivitas menyeru kepada sesama manusia, Allah SWT telah memberikan panduan, “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan cara yang baik..” (QS. An Nahl: 125).
Bila kita mampu menerapkan hal di atas, maka kritik kita insya Allah bernilai ibadah, mendatangkan pahala, dan akan memberi kebaikan bagi orang yang dikritisi. Menjadi tanggung jawab bagi setiap Muslim untuk menghidupkan kewajiban muhasabah lil hukkam. Terutama kalangan pemuda dan intelektual karena mereka adalah martir kebangkitan umat. Meskipun sistem dan rezim saat ini represif, pantang menyurutkan umat Islam menyuarakan kebenaran. Apa pun risikonya, cukuplah balasan terbaik dari Allah SWT.
Pesan Rasulullah Saw berikut menjadi indah untuk diingat. “Pemimpin syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri menghadap pemimpin yang zalim untuk melakukan amar makruf nahi mungkar, lalu penguasa itu pun membunuhnya.” (HR. Al-Hakim)
Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum dan Masyarakat) dan Puspita Satyawati (Analis Politik dan Media)